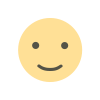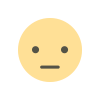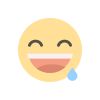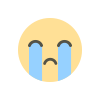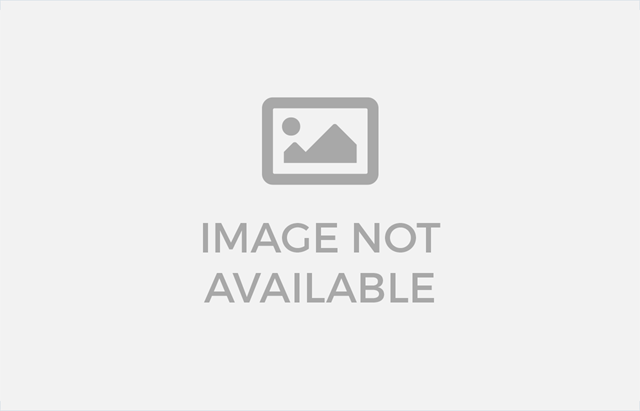Etika Kekuasaan Penguasa yang Semakin Tidak Etis
Kekuasaan yang dititipkan digunakan untuk melanggengkan ambisi kekuasaan, dengan cara-cara yang tidak lagi menghormati kedaulatan rakyat.

Liberty may be endangered by the abuse of liberty, but also by the abuse of power (James Madison).
BEBERAPA waktu belakangan, kita acapkali menyaksikan permainan kekuasaan sangat kentara yang terus mencoba merekayasa arah politik elektoral agar hasil akhir pemilihan sesuai dengan selera jejaring penguasa yang sedang bertakhta.
Sangat miris memang. Kekuasaan yang dititipkan dengan tulus oleh rakyat lebih kurang empat tahun lalu, pada akhirnya digunakan untuk melanggengkan ambisi kekuasaan, dengan cara-cara yang tidak lagi menghormati kedaulatan rakyat. Etika politik ditabrak, rambu-rambu moral demokrasi diabaikan.
Fase inilah sebenarnya yang menjadi salah satu fase yang dikhawatirkan oleh James Madison, sebagaimana penulis kutip di awal tulisan.
Indonesia selama ini selalu berhasil membendung kebebasan mutlak dengan berbagai cara dan pasal dalam perundangan agar tidak terjadi anarki politik di level akar rumput.
Namun, sejarah juga membuktikan bahwa Indonesia pernah tercatat mengalami kesulitan keluar dari siklus penyalahgunaan kekuasaan, membuat sejarah negeri ini akhirnya hanya didominasi oleh cerita penguasa-penguasa yang berusaha untuk tetap berkuasa.
Jika tidak bisa bertahan berkuasa secara langsung, maka secara tidak langsung pun tak masalah.
Imbasnya, di satu sisi kebebasan politik digaungkan sebagai landasan utama dalam dinamika elektoral. Di sisi lain, kekuasan dimainkan dan direkayasa untuk membuat kebebasan politik masyarakat kehilangan pengaruh di dalam menentukan arah politik negeri ini.
Perpaduan jejaring kuasa dan modal dihadirkan secara telanjang untuk membuat pilihan rakyat tak lagi berdasarkan hati nurani, tapi berdasarkan godaan-godaan "post truth" yang diproduksi secara masif untuk mengaburkan fakta-fakta yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh pemilih dalam memilih.
Lihat saja, sejak awal Presiden Jokowi dengan santai mengabaikan banyak prinsip-prinsip etika politik, terutama terkait dengan keputusannya membiarkan Gibran Rakabuming Raka ikut ke dalam arena kontestasi Pilpres 2024.
Keputusan membiarkan, bahkan mendukung, tindakan Gibran tersebut sebenarnya secara moral adalah pelanggaran etika politik paling besar yang dilakukan Presiden Jokowi, karena membuka jalan bagi lahirnya dinasti politik baru di negeri ini yang didukung langsung tanpa tedeng aling-aling oleh jejaring kekuasaan yang sedang berkuasa.
Sementara penerobosan asas-asas etika lainnya setelah itu mengikuti dengan sangat telanjang juga, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembelaan atas pelanggaran etika pertama dan terbesar tersebut, semacam membela kesalahan dengan kesalahan-kesalahan baru.
Pasalnya, untuk menutupi dan membela kesalahan tidak mungkin dengan kebenaran, sudah pasti dengan kesalahan-kesalahan baru.
Jadi pelanggaran etika pertama tersebut akan menjadi justifikasi bagi presiden untuk melakukan pelanggaran etika lainnya sampai pemilihan umum selesai, termasuk soal pernyataan "off side" presiden yang mengatakan bahwa presiden boleh ikut berkampanye, boleh memihak, dan sejenisnya, meskipun tidak memakai fasilitas negara.
George W. Bush atau Bush Yunior tak pernah terlibat dalam kampanye John McCain untuk melawan Obama tahun 2008.
Obama pun sama. Obama tak pernah menunjukkan sikap keberpihakan secara terbuka untuk Hillary Clinton, karena ia mengetahui bahwa statusnya sebagai kepala negara, kepala Pemerintahan, dan panglima tertinggi, tak akan benar-benar bisa dilepaskan. Etika politiknya memang demikian.
Jadi masalahnya dengan pernyataan Presiden Jokowi tersebut adalah bahwa ada banyak fasilitas negara yang tidak bisa lepas dari seorang presiden, dalam kondisi apapun, termasuk kondisi kampanye menjelang pemilihan umum.
Fasilitas tersebut hanya diperbolehkan tetap melekat ketika seorang presiden ikut berkontestasi. Artinya, selama yang berkontestasi tersebut adalah presiden itu sendiri, maka presiden boleh berkampanye dengan beberapa fasilitas negara yang tetap melekat pada dirinya.
Misalnya, saat Pilpres 2019, di mana Jokowi sedang mempertahankan kekuasaannya secara legal konstitusional untuk periode kedua. Namun saat ini kondisinya berbeda. Jokowi tidak sedang berkontestasi. Yang berkontestasi hanya anaknya, yang tidak memiliki wewenang seperti dirinya.
Artinya situasinya sangat berbeda. Jika Jokowi ikut memihak dan berkampanye, maka lapangan pemilihan mendadak tidak berada pada posisi level playing field lagi, karena Jokowi sedang memegang kekuasaan besar, yang bisa saja digunakan untuk melemahkan kontestan lain.
Masalah kedua adalah bahwa presiden, bagaimanapun, tidak boleh ikut berpolitik dan berkampanye. Yang boleh ikut berkampanye dan memihak adalah "Jokowi" secara orang per orang atau pribadi seorang Jokowi.
Karena jabatan presiden adalah bagian dari kelembagaan kepresidenan atau "presidency", yang sifatnya harus netral secara institusional.
Nah, karena banyak fasilitas negara yang melekat atau tidak bisa dilepaskan dari seorang presiden, dalam kondisi apapun, karena itulah mengapa seorang presiden tak boleh memihak dan berkampanye, kecuali ia sendiri yang ikut berkontestasi seperti tahun 2019.
Etika demokrasi akan seketika tercederai jika presiden ikut ke lapangan politik, tapi sebenarnya beliau bukan pemain lagi.
Artinya, tidak mungkin melepaskan "Jokowi" secara personal dari jabatannya sebagai presiden, karena ia masih menjabat.
Tidak mungkin Jokowi tanpa wewenang presiden, tanpa para pembantunya bernama menteri, tanpa Paspampres, tanpa mobil dinas, tanpa pesawat kepresidenan, tanpa ini itu lainnya, karena tanpa itu semua, Jokowi baru bisa menjadi Jokowi non presiden.
Jadi pengunaan kata presiden boleh berkampanye saja sudah salah secara etika dan etimologis, apalagi mempraktikkannya secara terang-terangan.
Namun nahasnya bagi demokrasi kita, semua pelanggaran etika yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini terjadi di ranah sangat abu-abu.
Jokowi berusaha bermain petak umpet dengan aturan, bermain di ranah yang tidak bisa dituntut secara legal karena tidak tertulis secara jelas. Yang dilanggar Jokowi selama ini adalah nilai-nilai etika konvensional, yang kebanyakan tidak tertulis secara baku.
Ibarat nilai dan norma yang sering diajarkan kepada kita sewaktu kecil, seperti ajaran "tidak boleh melawan kepada yang tua", misalnya. Namun tak ada aturan tertulis yang melarang anak menolak perintah orangtua atau melawan kepada orangtua, meskipun semua orang di Indonesia mengetahui bahwa tindakan itu salah.
Toh nyatanya tak ada yang sempat berpikir kalau Jokowi akan melawan ke PDIP dan Megawati Soekarnoputri, tapi nyatanya Jokowi melakukan itu.
Padahal, jika ada anak-anak yang melawan kepada orangtua, maka akan dilabeli sebagai anak durhaka. Beruntung bagi Jokowi, PDIP masih belum melabelinya sebagai anak durhaka.
Lalu, belum usai soal kontroversi presiden boleh berkampanye, Jokowi kembali menggemparkan publik dengan rencana pemberian BLT dadakan atas nama mitigasi risiko tekanan ekonomi. Angkanya mendadak naik, waktunya dikebut.
BLT yang seharusnya enam bulan, dikebut dalam sekali pencairan. Secara etika, kebijakan semacam ini adalah pelanggaran etis yang akut. Tak ada angin tak ada hujan, kebijakan berubah mendadak.
Sebenarnya publik juga memahami bahwa logika bansos memang untuk menahan agar pertumbuhan ekonomi tidak mengalami penurunan lebih lanjut. Jadi dalam konteks ini, bansos memang bisa dimengerti.
Pasalnya, sebagaimana diketahui dari data PDB beberapa kuartal terakhir, pertumbuhan terus mengalami penurunan. Utamanya pertumbuhan konsumsi rumah tangga melambat alias tercatat kurang menggembirakan.
Artinya, ada masalah dengan daya beli masyarakat, terutama karena inflasi untuk beberapa komoditas pokok.
Karena itu, dalam konteks ekonomi, cukup bisa dipahami mengapa pemerintah memilih opsi intervensi dengan berbagai macam bansos, agar tekanan daya beli tak terlalu memberatkan kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Sekali lagi, dalam konteks ini, tentu tak ada masalah. Saya yakin, semua ekonom akan memahami hal tersebut, karena memang intervensi dibutuhkan jika ekonomi tak berjalan sebagaimana harapan.
Namun jika dilakukan secara dadakan, maka bukan saja etika politik yang ditabrak, etika fiskalpun akan ternodai.
Dan masalah menjadi semakin aneh karena ada potensi kepentingan politik eletoral yang bersembunyi di balik keputusan bansos tersebut. Jika saja Jokowi tidak berpihak ke salah satu kandidat atau tidak memperlihatkan keberpihakannya secara terbuka, maka tentu tak ada masalah.
Namun nyatanya tidak demikian. Presiden Jokowi secara de facto memang berpihak, bahkan sempat menyatakan bahwa presiden memang boleh memihak, yang serta merta membuat semua kebijakan bansos mau tak mau berpengaruh secara elektoral ke salah satu paslon, yakni paslon yang didukung presiden.
Walhasil, kebijakan bansos berpeluang menjadi instrumen "pork barrel politic", yakni memakai anggaran negara untuk program dan kebijakan intervensionis, yakni kebijakan sosial kesejahteraan, baik dalam skala lokal maupun nasional, yang berpeluang untuk menguntungkan salah satu paslon secara elektoral. Di sinilah masalah itu muncul dan mulai dipersoalkan oleh banyak pihak.
Dan karena itulah, mengapa semestinya para paslon harus nonaktif dari segala jabatannya di pemerintahan, agar tidak terjadi "spill over" elektoral dari kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Sayangnya, ternyata itu tak terjadi.
Pun karena itu pula kenapa seorang presiden, yakni presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, seharusnya berposisi netral-senetralnya, agar pemilihan umum berada pada level playing field yang sama untuk semua paslon alias tidak ada calon yang menjadi "free rider" atas kebijakan bansos pemerintah.
Pendeknya, Jokowi sebagai presiden sama sekali sudah abai pada etika politik di dalam negara yang tercatat sebagai negara demokrasi terbesar kedua di Asia, setelah India, demi memastikan keberlanjutan kekuasaannya kepada paslon yang ia inginkan, di mana anak sulungnya menjadi calon wakil presiden.
Jika kita kaitkan dengan pernyataan James Madison di atas, Jokowi sebenarnya telah melakukan hal yang sangat menakutkan dengan kekuasaannya, yakni menyalahgunakan kekuasaan di satu sisi dan mengopresi perbedaan secara halus di sisi lain, dengan mempersulit paslon lain untuk bersaing secara fair sekaligus melemahkan suara-suara kritik kepada pemerintah.
Apa yang dipertontonkan Presiden Jokowi, sudah mulai ditiru oleh anaknya di dalam dua kali debat cawapres. Etika politik dalam berdebat dengan orang yang lebih tua dilewati begitu saja.
Sikap Gibran terlihat sangat merendahkan lawan debatnya yang notabene jauh lebih tua dan lebih senior.
Bahkan Gibran berusaha untuk menunjukkan kepada publik bahwa lawan debatnya "tidak mengetahui apa-apa", sebagai upaya pengalihan dari perdebatan substantif yang sebanarnnya sangat dibutuhkan penonton.
Pertanyaanya kemudian, bagaimana imbas dari masalah etika seorang presiden terhadap pemilih mayoritas, yakni pemilih milenial dan generasi Z? Semoga tidak seperti yang saya takutkan. Semoga!
Apa Reaksi Anda ?