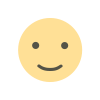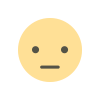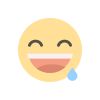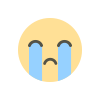30 Tahun Genosida Rwanda yang Menewaskan 800 Ribu Orang
PBB memperkirakan 800.000 warga Rwanda tewas dalam genosida yang terjadi selama 100 hari pada tahun 1994.

GENOSIDA di Rwanda merupakan salah satu kasus genosida paling banyak memakan korban di dunia. Tragedi yang terjadi selama 100 hari dari April sampai dengan Juli 1994 itu memakan lebih dari 800.000 korban jiwa. Sebanyak dua juta orang Rwanda juga dilaporkan meninggalkan negara itu pada saat genosida tersebut terjadi.
Aksi genosida itu dilakukan oleh suku mayoritas di Rwanda, yaitu suku Hutu, yang saat itu memiliki keinginan untuk menghabisi seluruh suku minoritas Tutsi di sana. Tidak hanya orang-orang Tutsi, orang-orang Hutu moderat atau mereka yang menentang genosida tersebut juga ikut menjadi target dalam tragedi itu.
Baca juga: Salah Satu Buron Terakhir Genosida Rwanda Dipastikan Tewas
Latar Belakang
Ada tiga kelompok suku di Rwanda. Namun empat dari lima orang Rwanda berasal suku Hutu. Di sisi lain, terdapat suku Tutsi yang menempati posisi kedua dengan satu dari tujuh populasi Rwanda adalah orang Tutsi. Suku ketiga adalah Twa yang hanya sekitar satu persen populasi di Rwanda. Ketiga kelompok itu berbicara dalam bahasa yang sama dan telah hidup berdampingan selama berabad-abad.
Wilayah Rwanda berdiri sekarang diyakini dihuni pertama kali oleh suku Twa, baru oleh suku Hutu antara abad ke-5 dan ke-11, kemudian disusul oleh suku Tutsi kemungkinan pada abad ke-14.
Tahun 1898 sampai dengan 1916, Jerman menduduki wilayah Rwanda. Pada periode ini, pemerintah kolonial Jerman menerapkan kebijakan pemerintahan yang secara tidak langsung memperkuat hegemoni kelas penguasa Tutsi. Hal ini terus berlanjut sampai dengan Rwanda jatuh ke tangan Belgia setelah Perang Dunia I.
Beberapa orang suku Hutu mulai menuntut kesetaraan dan hal ini mendapat simpati dari pastor Katolik Roma serta beberapa pegawai administrasi Belgia. Fenomena inilah yang kemudian mendorong revolusi Hutu tahun 1959. Revolusi dimulai tepatnya pada 1 November ketika tersebar rumor kematian pemimpin Hutu di tangan orang-orang Tutsi.
Selama berbulan-bulan, kekerasan terus terjadi, menyebabkan banyak orang Tutsi terbunuh atau meninggalkan negara itu. Pada 28 Januari 1961, suku Hutu melancarkan kudeta. Dengan persetujuan rahasia dari otoritas kolonial Belgia, mereka berhasil menggulingkan raja Tutsi yang saat itu sudah melarikan diri pada tahun 1960.
Setelah kudeta, mereka menghapuskan monarki dan menjadikan Rwanda negara republik. Pada saat itu juga mereka membentuk pemerintahan nasional sementara yang seluruhnya terdiri dari orang-oramg Hutu. Tahun berikutnya, kemerdekaan pun diproklamasikan.
Meski begitu, pertumpahan darah masih terus berlangsung di Rwanda. Ketegangan dan kekerasan antara etnis Tutsi dan Hutu kembali terjadi secara berkala seperti pada tahun 1963, 1967, dan 1973. Ketegangan antara kedua suku tersebut kembali memanas tahun 1990 ketika kelompok pemberontak yang dipimpin Tutsi, Rwandan Patriotic Front (RPF) menyerbu dari Uganda.
Gencatan senjata dinegosiasikan pada awal tahun 1991. Setahun setelahnya, RPF dan pemerintahan Presiden Rwanda saat itu, Juvenal Habyarimana, memulai negosiasi yang kemudian menghasilkan sebuah perjanjian yang ditandatangani pada Agustus 1993 di Arusha, Tanzania. Perjanjian ini secara garis besar menyangkut pembentukan pemerintahan yang akan mencakup RPF.
Baca juga: Felicien Kabuga Tersangka Penghasut Genosida Rwanda Akan Dibebaskan
Ekstremis Hutu menentang perjanjian itu. Sebagai respon, mereka menyebarkan agenda anti-Tutsi melalui surat kabar dan stasiun radio yang berujung pada kekerasan etnis.
Pada 6 April 1994, pesawat yang membawa Presiden Habyarimana dan Presiden Burundi, Cyprien Ntaryamira, ditembak jatuh di Kigali. Semua yang ada di pesawat tersebut tewas.
Tidak pernah diklarifikasi siapa yang menembak jatuh pesawat tersebut. Walau begitu, media lokal menyalahkan RPF atas tragedi itu dan menginstruksikan agar suku Hutu segera mengambil tindakan. Insiden inilah yang menandai awal dari puncak ketegangan antara Tutsi dan Hutu, yang berujung pada aksi Genosida Rwanda.
Pembunuhan Dilakukan Secara Teratur dan Bertahap
Genosida Rwanda terjadi secara bertahap. Tragedi ini diawali oleh pembunuhan Perdana Menteri Agathe Uwilingiyimana yang merupakan seorang Hutu moderat. Uwilingiyimana dibunuh bersama 10 penjaga perdamaian Belgia yang ditugaskan untuk melindunginya di rumahnya pada 7 April 1994 hanya beberapa jam setelah media menyiarkan pembunuhan presiden dan mengorelasikannya dengan RPF.
Setelah itu, pasukan pemerintah bersama dengan kelompok milisi Hutu yang dikenal sebagai Interahamwe (memiliki arti “mereka yang menyerang bersama”) mulai memasang penghalang jalan dan barikade di Kigali lalu menyerang orang-orang Tutsi dan Hutu moderat.
Tentara menembaki massa sementara orang-orang yang tergerak oleh pesan-pesan media serta dijanjikan imbalan oleh pemerintah mendatangi rumah-rumah dan membunuh setiap orang Tutsi yang mereka ketahui, termasuk orang Hutu yang menawarkan perlindungan kepada orang Tutsi. Tidak sedikit yang bahkan membunuh tetangga dan anggota keluarga mereka sendiri. Ada pula yang memperkosa perempuan dan menjarah rumah. Banyak korban juga digiring ke area terbuka dan dibunuh di sana secara bersamaan.
Aksi pembunuhan massal berakhir setelah 100 hari, tepatnya pada 4 Juli ketika RPF berhasil menguasai Kigali. Orang-orang Hutu yang terlibat dalam genosida serta warga Hutu lainnya yang takut akan pembalasan melarikan diri dari negara tersebut ke Kongo. Pejabat pemerintah mengambil kas negara dan ikut melarikan diri ke Prancis.
Peran Media Dalam Genosida Rwanda
Ada dua stasiun radio paling dominan di Rwanda, yaitu Radio-Television Libres des Milles Collines (RTML) dan Radio Rwanda yang dimiliki negara. Keduanya memainkan perang krusial dalam memperburuk kebencian terhadap suku Tutsi di Rwanda. Kedua stasiun radio tersebut aktif menyebarkan pesan-pesan yang meningkatkan ketakutan di kalangan Hutu terhadap RPF.
RTML contohnya, mereka sering mengeluarkan pernyataan yang merendahkan suku Tutsi dengan kata-kata seperti “orang-orang itu adalah kelompok kotor” di tengah-tengah pemutaran lagu. Mereka juga sering menggunakan istilah seperti “kecoak” dan “ular” saat mendeskripsikan suku Tutsi. RTML menjadi stasiun radio pertama yang mengorelasikan pembunuhan presiden kepada RPF.
Selama genosida, para penyerang berparade di jalan-jalan dengan parang di satu tangan dan radio di tangan yang lain. Stasiun radio yang mereka dengarkan adalah Radio Rwanda dan RLTM yang kala itu melalui siarannya mengumumkan nama-nama orang Tutsi dan pelindung-pelindung mereka agar para penyerang tahu di mana dapat menemukan mereka.
Jumlah Korban Tidak Diketahui Pasti
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan 800.000 warga Rwanda tewas dalam genosida tersebut. Pemantau independen lain mengatakan jumlah korban hanya sekitar 500.000 orang.
Sampai saat ini, kuburan massal korban Genosida Rwanda masih kerap ditemukan di penjuru Rwanda. Itu sebabnya jumlah korban masih belum dapat dipastikan. Apa lagi, jumlah populasi Tutsi setelah genosida juga tidak dapat dipastikan dengan jelas karena banyak dari mereka mengaku Hutu demi menghindari pembunuhan. Pemerintah Rwanda pasca genosida juga menghapuskan identifikasi yang menunjukan etnis di dalam sensusnya.
Sensus tahun 1991 memperkirakan populasi Tutsi berjumlah 657.000, atau 8,4 persen dari total keseluruhan populasi Rwanda. Human Rights Watch memperkirakan setidaknya 500.000 orang Tutsi atau 77 persen dari populasi mereka pada tahun 1991 tewas terbunuh.
Desa Rekonsiliasi
Di tahun 2005, pemerintah bersama dengan Prison Fellowship Rwanda, sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM), membangun enam desa rekonsiliasi di seluruh penjuru Rwanda. Pembentukan desa-desa ini diharapkan dapat membangun kembali kehidupan bersama mereka.
Desa-desa ini juga diharapkan dapat menciptakan kesetaraan antara kedua kelompok etnis serta mencegah orang melakukan balas dendam atas genosida tahun 1994 itu.
Salah satu desa rekonsiliasi itu adalah Desa Mbyo di mana Al Jazeera berbicara dengan Mukaremera Laurence, penyintas genosida yang hidup berdampingan dengan pembunuh suaminya pada saat insiden genosida, Nkundiye Thacien. Sebelum genosida, mereka merupakan tetangga yang berteman baik. Namun di tahun 1994, Thacien mengaku mendapat perintah untuk membunuh. Salah satu korbannya tak lain adalah suami dari tetangganya itu.
“Itu adalah perintah dan jika Anda tidak mematuhinya, mereka mengancam akan membunuh keluarga Anda,” kata Thacien kepada Al Jazeera. “Jadi saya merasa harus melakukannya.”
Laurence baru mengetahui bahwa yang membunuh suaminya adalah Thacien di tahun 2003 setelah Thacien menulis surat kepadanya dari penjara dan mengakui perbuatannya.
Pemerintah saat itu telah mengadopsi undang-undang yang mengizinkan pengurangan hukuman penjara jika pelaku mau mengakui telah terlibat atas pembunuhan tersebut.
“Saya merasa sangat bersalah bahkan ketika saya melakukannya, namun di penjara saya tahu saya harus menghadapi tindakan saya,” kata Thacien.
Ketika Laurence menerima surat tersebut dan mengetahui bahwa orang yang membunuh suaminya adalah teman dan tetangganya, Laurence sangatlah terkejut.
“Sangat sulit bagi saya untuk membaca surat itu,” kata Laurence kepada Al Jazeera, “Saya tidak dapat membayangkan atau memahami apa yang terjadi dan mengapa.” Laurence juga mengaku khawatir pembebasan kembali tahanan ke masyarakat akan menempatkannya dalam bahaya menjadi sasaran milisi Hutu lagi.
Meski begitu, kini Thacien dan Laurence hidup berdampingan dengan damai di Desa Mbyo.
Apa Reaksi Anda ?